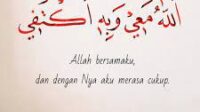Oleh : Mustaqiem Eska
(pdlFile.com) – Dalam lanskap kesusastraan Indonesia yang kaya dan beragam, sebuah fenomena unik kerap kali menyelimuti para empu pena: keengganan untuk mencantumkan nama lengkap, apalagi gelar akademis, dalam setiap jejak karya yang mereka torehkan. Bahkan, tak jarang kita jumpai inisial misterius yang justru menambah aura anonimitas. Lebih jauh lagi, latar belakang pendidikan formal para sastrawan seolah menjadi tabu untuk diperbincangkan, tenggelam dalam arus deras karya-karya yang mereka lahirkan. Kita mungkin akrab dengan puisi-puisi Chairil Anwar yang penuh gejolak, esai-esai Sutan Takdir Alisjahbana yang visioner, lirik-lirik puitis layaknya Sapardi Djoko Damono, WS. Rendra, Emha Ainun Nadjib, hingga Mustofa Bisri yang menyuburkan sastra Indonesia. Namun informasi mendetail mengenai pendidikan formal mereka seringkali luput dari perhatian publik. Seolah ada ruh kesusastraan yang alergi terhadap atribut-atribut duniawi seperti gelar, padahal kenyataannya, banyak di antara mereka adalah sosok-sosok terpelajar.
Fenomena ini tentu mengundang pertanyaan. Apakah keengganan ini merupakan sebuah kesadaran filosofis, penolakan terhadap formalitas yang dianggap membatasi kebebasan ekspresi? Atau justru sebuah strategi untuk memfokuskan pembaca sepenuhnya pada karya, tanpa terdistraksi oleh identitas personal dan capaian akademis sang penulis?
Salah satu interpretasi yang mungkin adalah bahwa bagi para sastrawan, esensi karya terletak pada resonansi yang ditimbulkannya dalam jiwa pembaca, bukan pada siapa yang menciptakannya. Nama dan gelar, dalam konteks ini, dapat dianggap sebagai sekat yang justru menjauhkan pembaca dari pengalaman murni berinteraksi dengan teks. Karya sastra, layaknya sungai yang mengalir bebas, seharusnya dapat diakses dan diresapi oleh siapa saja yang memiliki kepekaan untuk menangkap pesannya. Dengan menyembunyikan identitas personal, para sastrawan seolah menyerahkan karya mereka pada anonimitas kolektif, membiarkannya tumbuh dan berkembang di benak setiap individu yang membacanya.
Penggunaan inisial, di sisi lain, bisa jadi merupakan sebuah kompromi antara keinginan untuk tetap hadir sebagai entitas pencipta dan hasrat untuk menjaga jarak dari sorotan personal. Inisial menjadi semacam jejak samar, cukup untuk menandai kepemilikan karya namun tidak cukup untuk mengundang rasa ingin tahu berlebihan terhadap kehidupan pribadi. Ini sejalan dengan pandangan bahwa yang utama adalah karya itu sendiri, bukan sosok di baliknya.
Keengganan untuk menonjolkan latar belakang pendidikan formal juga menarik untuk dicermati. Mungkin para sastrawan menyadari bahwa keindahan dan kekuatan sebuah karya tidak selalu berbanding lurus dengan tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh. Inspirasi dan kepekaan artistik seringkali muncul dari pengalaman hidup, perenungan mendalam, dan interaksi dengan realitas sosial, hal-hal yang tidak selalu dapat diukur oleh gelar akademis. Dengan tidak menekankan pendidikan formal, para sastrawan seolah ingin menegaskan bahwa legitimasi mereka sebagai penulis terletak pada kualitas karya yang mereka hasilkan, bukan pada deretan huruf di belakang nama.
Selain itu, dalam konteks budaya Indonesia yang mungkin memiliki pandangan tersendiri terhadap kepopuleran dan ketenaran, sikap merendah dan tidak menonjolkan diri bisa jadi merupakan bagian dari etos kesenian. Fokus pada karya semata, tanpa embel-embel personal, mencerminkan sebuah dedikasi yang tulus terhadap dunia literasi.
Tentu saja, interpretasi ini tidak bersifat mutlak. Setiap sastrawan memiliki motivasi dan latar belakang unik yang membentuk pilihan mereka dalam berinteraksi dengan publik. Namun, fenomena keengganan mencantumkan nama lengkap dan latar belakang pendidikan ini tetap menjadi ciri khas yang menarik dalam tradisi sastra Indonesia. Ia mengisyaratkan sebuah pemahaman mendalam tentang hakikat karya seni yang seharusnya melampaui identitas personal penciptanya, sebuah undangan bagi pembaca untuk menyelami makna tanpa terbebani oleh informasi biografis. Misteri di balik pena ini justru memperkaya pengalaman membaca, membiarkan karya berbicara lebih lantang daripada nama dan gelar sang pengarang.***